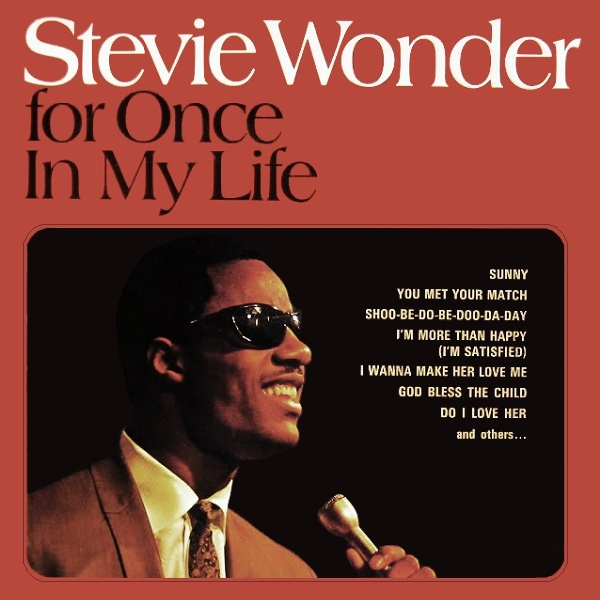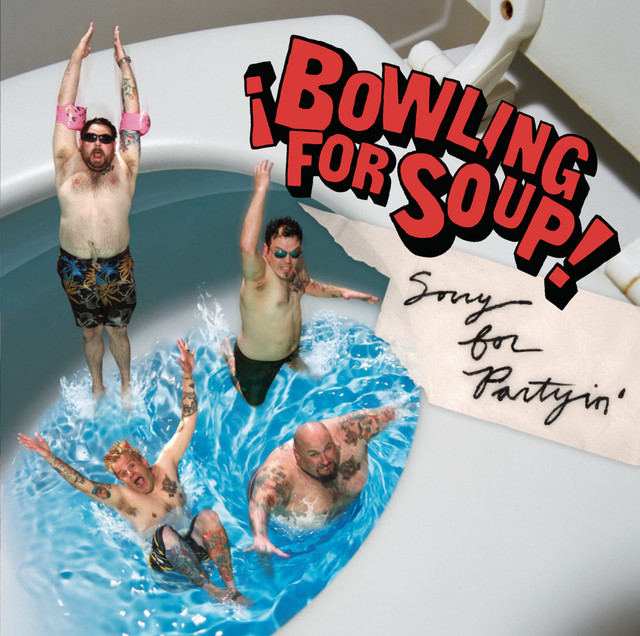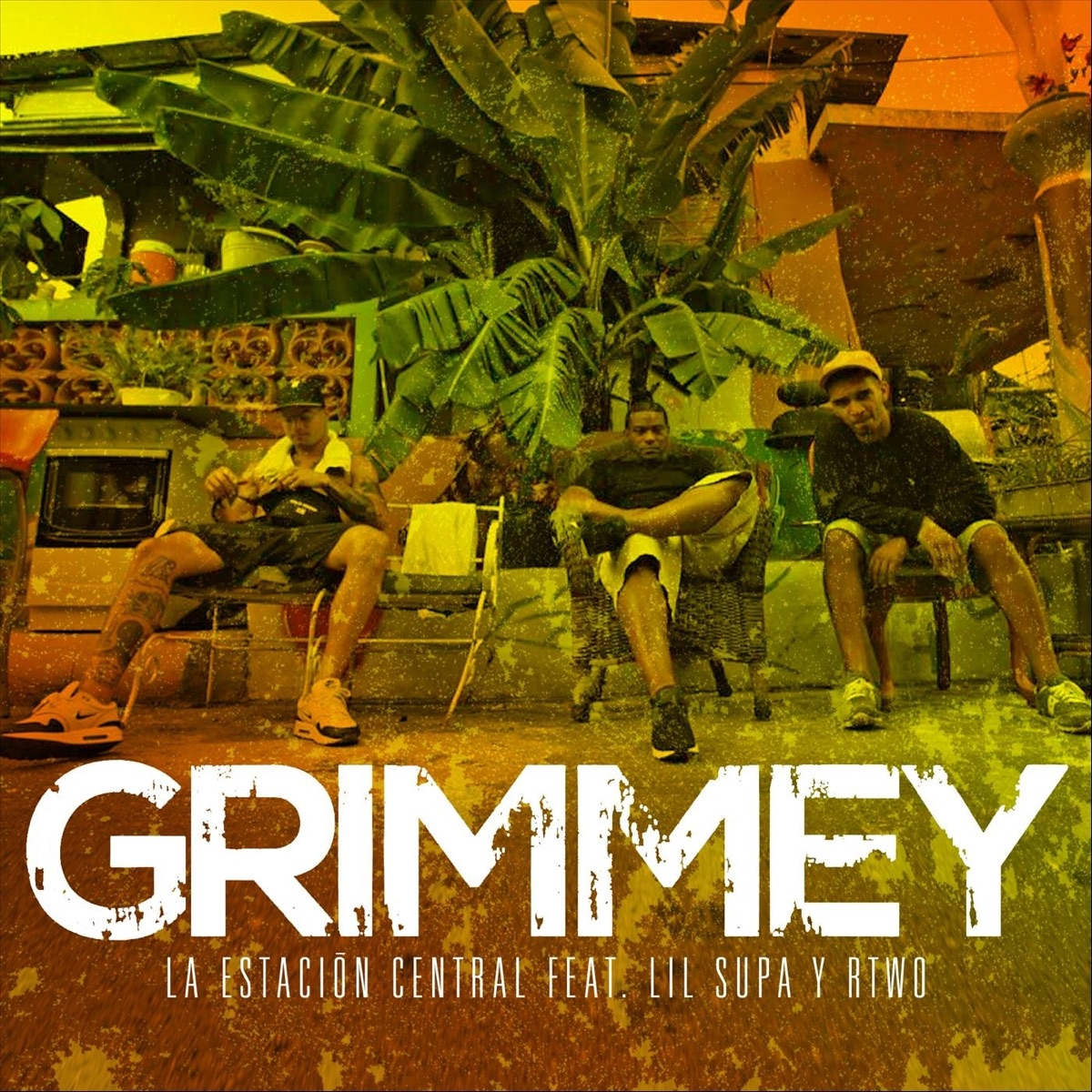Edgar Allan Poe - The Tell-Tale Heart - Terjemahan Indonesia Lyrxo Terjemahan Indonesia
На этой странице вы найдете полный текст песни "Edgar Allan Poe - The Tell-Tale Heart - Terjemahan Indonesia" от Lyrxo Terjemahan Indonesia. Lyrxo предлагает вам самый полный и точный текст этой композиции без лишних отвлекающих факторов. Узнайте все куплеты и припев, чтобы лучше понять любимую песню и насладиться ею в полной мере. Идеально для фанатов и всех, кто ценит качественную музыку.

Sumpah, aku tidak mengerti kenapa kalian menganggapku gila. Penyakitku ini bukannya menumpulkan atau menghancurkan panca inderaku, tapi malah menajamkannya. Yang paling dibuatnya tajam adalah indera pendengaranku. Aku dapat mendengar apapun yang ada di langit dan bumi, terutama di neraka. Jadi, bagaimana mungkin aku gila? Kalau kalian masih juga tidak percaya, maka perhatikanlah betapa warasnya dan tenangnya aku mengisahkan seluruh cerita ini.
Aku juga masih tidak tahu pasti sejak kapan ide itu muncul dalam benakku, tapi segera setelah ide itu tertanam dalam otakku, aku selalu merasa ada yang menghantuiku sepanjang siang dan malam, sehingga aku tidak dapat menolak untuk melakukannya.
Sebenarnya aku menyayangi orang tua itu. Lagipula dia juga tidak pеrnah menyakiti ataupun menyinggungku. Aku melakukannya bukan karеna hartanya, tapi karena matanya! Ya, benar. Matanya! Dia memiliki mata bak burung vulture dengan warna biru pucat. Setiap kali dia menatapku, darahku langsung membeku. Akhirnya lama kelamaan, aku memutuskan untuk mencabut nyawanya agar aku dapat terbebas dari pandangan matanya.
Sekarang intinya begini; kalian menganggapku gila, tapi orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Seharusnya kalian melihat betapa hati-hati dan elegannya caraku berjalan ke tempat kerja! Selama seminggu sebelum aku membunuhnya, aku bersikap sangat ramah terhadapnya. Setiap malam, aku membuka grendel pintu kamarnya—oh pelan sekali! Kemudian kubuka pintunya sedikit lalu kumasukkan kepalaku. Oh, kau pasti akan tertawa melihat betapa cerdiknya aku melakukannya! Aku bergerak dengan perlahan—amat sangat perlahan agar tidak mengganggu tidurnya. Butuh waktu satu jam bagiku untuk dapat memasukkan seluruh kepalaku celah yang terbuka itu sampai aku dapat melihatnya sedang berbaring di atas ranjang. Ha! Kalian pikir orang gila bisa secerdik ini? Kemudian, ketika seluruh kepalaku sudah masuk ke dalam kamarnya, kuputar tuas lenteraku dengan hati-hati—oh, aku melakukannya dengan amat sangat hati-hati karena tuasnya dapat mengeluarkan bunyi decitan. Kuputar lenteraku sampai dapat menerangi mata sipitnya dengan seberkas cahaya redup. Dan ini kulakukan selama seminggu penuh—tepat saat tengah malam—tapi matanya selalu tertutup, sehingga tidak mungkin aku membunuhnya. Karena bukan orang tua itu yang menjengkelkanku, tapi Mata Kejinya itu. Dan setiap pagi, ketika hari mulai petang, secara terang-terangan aku pergi ke kamarnya dengan gagah berani lalu memanggil namanya dengan nada menyentuh hati, dan menanyakan bagaimana tidurnya malam tadi. Jadi, kalian tahu sendiri ‘kan? Kalau tidak begitu, dia bisa curiga kalau setiap malam, tepat jam dua belas malam, aku selalu menatapnya saat dia tertidur.
Pada malam kedelapan, aku lebih berhati-hati daripada biasanya saat membuka pintu. Jarum jam yang menunjukkan menit bergerak lebih cepat. Sebelumnya tidak pernah aku merasakan batas kekuatanku—atau kecerdikanku. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Bayangkan saja, aku di sana, membuka pintunya sedikit demi sedikit, dan dia bahkan tidak pernah mengira atau membayangkan hal yang kulakukan ini. Aku sedikit terkekeh dibuatnya. Dia mungkin dapat mendengar suara tawaku, karena tiba-tiba dia bergerak di atas ranjangnya seakan terkejut oleh sesuatu. Sekarang kalian mungkin berpikir aku akan berlari keluar—tapi tidak. Kamarnya segelap dan setebal kegelapan malam, (karena tirai jendelenya tertutup rapat untuk menghindari pencurian) dan dari sanalah aku yakin kalau dia tidak dapat melihat pintunya terbuka, sehingga aku terus membukanya pelan-pelan.
Kepalaku telah masuk, dan saat kucoba menyalakan lentera, jariku terpeleset di tuasnya. Kemudian orang tua itu terbangun sambil berteriak—“Siapa di sana?”
Aku berdiri bak patung dan bungkam. Selama satu jam penuh aku tidak bergerak sama sekali, dan sementara itu tidak pula aku mendengarnya berbaring kembali. Dia masih duduk di atas ranjangnya, mencoba mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Seperti yang biasanya kulakukan, malam demi malam, mendengarkan kematian yang selalu mengawasiku dari balik dinding.
Beberapa saat kemudian aku mendengar suara rintihan kecil, dan aku tahu bahwa itu adalah suara rintihan manusia yang ketakutan. Itu bukanlah rintihan kesakitan ataupun kesedihan—oh, bukan!—itu adalah suara cekikan lemah yang datang dari jiwa yang dilimpahi perasaan kagum. Aku tahu benar suara itu. Selama bermalam-malam, tepat saat tengah malam, ketika dunia tertidur, suara itu mengalir di dalam dadaku, semakin dalam, dengan gaungnya yang mengerikan bak teror yang selalu mengusikku. Sudah kubilang, aku tahu benar suara itu. Aku mengerti apa yang dirasakannya sehingga aku merasa simpati padanya, walaupun di dalam hati aku tertawa. Aku tahu kalau dia telah terbangun dari tadi semenjak mendengar suara ribut yang pertama. Ketakutan semakin membuncah di dalam dirinya. Dia mencoba menganggapnya bukan apa-apa, tapi tidak bisa. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri—“Tidak ada apa-apa, hanya suara angin yang bergerak di cerobong asap—atau hanya seekor tikus yang berlari di lantai,” atau “Itu hanya suara jangkrik yang mengerik satu kali.” Benar, dia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan anggapan-anggapan ini, tapi semuanya sia-sia. Karena Kematian telah mengikuti dalam bayang-bayang di depannya, kemudian menyelimuti korbannya. Dan pengaruh bayangan kasat mata itulah yang membuatnya dapat merasakan—walaupun dia tidak dapat melihat ataupun mendengarnya—kehadiran kepalaku di dalam kamar itu.
Ketika aku telah menunggu lama sekali, dengan sangat sabar, tanpa mendengarnya berbaring kembali, kuputuskan untuk memutar sedikit tuas lenteraku. Kalian tidak dapat membayangkan betapa diam-diamnya kulakukan itu—sampai seberkas cahaya redup menerangi mata sipitnya.
Matanya terbuka lebar! Kemudian aku menjadi kesal saat menatapnya. Tatapannya matanya membuatku bergetar sampai ke tulang sumsum. Tapi aku tidak dapat melihat bagian lain wajah atau tubuhnya selain mata kejinya, karena aku telah mengarahkan cahaya lenteraku tepat ke mata terkutuknya itu.
Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kau keliru menganggap kegilaan dengan ketajaman inderaku, bukan? Sekarang biar kujelaskan, telingaku mendengar sebuah suara rendah, tumpul, dan cepat seperti suara jam yang dibungkus kapas. Aku juga tahu benar suara apa itu. Itu adalah suara degupan jantungnya. Suaranya menaikkan amarahku seperti pukulan drum yang menyemangati para tentara di medan perang.
Tapi aku tetap menahan diri dan masih tidak bergerak. Napasku memburu tak beraturan. Kupegang erat lenteraku agar tidak bergoyang. Kucoba secara pasti mempertahankan cahaya yang menembak ke matanya. Sementara itu degupan jantungnya semakin menggebu. Semakin cepat dan lebih cepat lagi, dan semakin nyaring setiap detik. Dia pasti telah diselimuti oleh rasa takut yang amat sangat besar! Suaranya semakin nyaring setiap saat! Apa kau mengerti? Sudah kukatakan kalau aku mudah cemas. Dan sekarang, tepat saat tengah malam, di tengah-tengah keheningan rumah tua yang mengerikan, terasa sangat aneh saat suara seperti ini membuatku bersemangat menikmati ketakutannya yang tak terkendali. Namun begitu, selama beberapa menit aku masih menahan diriku dan tidak bergerak sedikit pun. Tapi degupannya semakin nyaring! Kurasa jantungnya pasti akan meledak. Dan sekarang kecemasan yang lain merengkuhku—suaranya mungkin dapat terdengar oleh tetangga! Waktu orang tua itu telah habis! Dengan teriakan keras, kuputar penuh tuas lenteraku dan melompat masuk ke dalam ruangan. Dia langsung menjerit tertahan. Dalam sekejap kuseret dia ke atas lantai, dan mengangkat kasurnya yang berat dan membekap tubuhnya dengan itu. Kemudian aku tersenyum riang karena sejauh ini perbuatanku telah selesai. Tapi selama beberapa menit, degupan jantungnya masih berdetak dengan suara teredam. Tapi ini tidak menjengkelkanku. Suaranya tidak akan terdengar melewati dinding. Suaranya akan menghilang setelah beberapa saat. Orang tua itu telah mati. Kugeser kasurnya untuk dapat mengamati mayatnya. Benar, dia telah mati kaku. Kuletakkan tanganku di atas dadanya agar dapat merasakan degup jantungnya selama beberapa menit. Tidak terasa adanya denyut nadi. Dia telah mati. Kini matanya tidak akan lagi menggangguku.
Jika kau masih berpikir aku gila, maka kau tidak akan lagi berpikir demikian saat kujelaskan tindakan cerdik yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam semakin larut, dan aku mengerjakannya dengan cepat namun tetap diam-diam. Pertama, kupisah-pisahkan anggota tubuhnya. Kupotong kepala, lengan, dan kakinya.
Aku juga masih tidak tahu pasti sejak kapan ide itu muncul dalam benakku, tapi segera setelah ide itu tertanam dalam otakku, aku selalu merasa ada yang menghantuiku sepanjang siang dan malam, sehingga aku tidak dapat menolak untuk melakukannya.
Sebenarnya aku menyayangi orang tua itu. Lagipula dia juga tidak pеrnah menyakiti ataupun menyinggungku. Aku melakukannya bukan karеna hartanya, tapi karena matanya! Ya, benar. Matanya! Dia memiliki mata bak burung vulture dengan warna biru pucat. Setiap kali dia menatapku, darahku langsung membeku. Akhirnya lama kelamaan, aku memutuskan untuk mencabut nyawanya agar aku dapat terbebas dari pandangan matanya.
Sekarang intinya begini; kalian menganggapku gila, tapi orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Seharusnya kalian melihat betapa hati-hati dan elegannya caraku berjalan ke tempat kerja! Selama seminggu sebelum aku membunuhnya, aku bersikap sangat ramah terhadapnya. Setiap malam, aku membuka grendel pintu kamarnya—oh pelan sekali! Kemudian kubuka pintunya sedikit lalu kumasukkan kepalaku. Oh, kau pasti akan tertawa melihat betapa cerdiknya aku melakukannya! Aku bergerak dengan perlahan—amat sangat perlahan agar tidak mengganggu tidurnya. Butuh waktu satu jam bagiku untuk dapat memasukkan seluruh kepalaku celah yang terbuka itu sampai aku dapat melihatnya sedang berbaring di atas ranjang. Ha! Kalian pikir orang gila bisa secerdik ini? Kemudian, ketika seluruh kepalaku sudah masuk ke dalam kamarnya, kuputar tuas lenteraku dengan hati-hati—oh, aku melakukannya dengan amat sangat hati-hati karena tuasnya dapat mengeluarkan bunyi decitan. Kuputar lenteraku sampai dapat menerangi mata sipitnya dengan seberkas cahaya redup. Dan ini kulakukan selama seminggu penuh—tepat saat tengah malam—tapi matanya selalu tertutup, sehingga tidak mungkin aku membunuhnya. Karena bukan orang tua itu yang menjengkelkanku, tapi Mata Kejinya itu. Dan setiap pagi, ketika hari mulai petang, secara terang-terangan aku pergi ke kamarnya dengan gagah berani lalu memanggil namanya dengan nada menyentuh hati, dan menanyakan bagaimana tidurnya malam tadi. Jadi, kalian tahu sendiri ‘kan? Kalau tidak begitu, dia bisa curiga kalau setiap malam, tepat jam dua belas malam, aku selalu menatapnya saat dia tertidur.
Pada malam kedelapan, aku lebih berhati-hati daripada biasanya saat membuka pintu. Jarum jam yang menunjukkan menit bergerak lebih cepat. Sebelumnya tidak pernah aku merasakan batas kekuatanku—atau kecerdikanku. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Bayangkan saja, aku di sana, membuka pintunya sedikit demi sedikit, dan dia bahkan tidak pernah mengira atau membayangkan hal yang kulakukan ini. Aku sedikit terkekeh dibuatnya. Dia mungkin dapat mendengar suara tawaku, karena tiba-tiba dia bergerak di atas ranjangnya seakan terkejut oleh sesuatu. Sekarang kalian mungkin berpikir aku akan berlari keluar—tapi tidak. Kamarnya segelap dan setebal kegelapan malam, (karena tirai jendelenya tertutup rapat untuk menghindari pencurian) dan dari sanalah aku yakin kalau dia tidak dapat melihat pintunya terbuka, sehingga aku terus membukanya pelan-pelan.
Kepalaku telah masuk, dan saat kucoba menyalakan lentera, jariku terpeleset di tuasnya. Kemudian orang tua itu terbangun sambil berteriak—“Siapa di sana?”
Aku berdiri bak patung dan bungkam. Selama satu jam penuh aku tidak bergerak sama sekali, dan sementara itu tidak pula aku mendengarnya berbaring kembali. Dia masih duduk di atas ranjangnya, mencoba mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Seperti yang biasanya kulakukan, malam demi malam, mendengarkan kematian yang selalu mengawasiku dari balik dinding.
Beberapa saat kemudian aku mendengar suara rintihan kecil, dan aku tahu bahwa itu adalah suara rintihan manusia yang ketakutan. Itu bukanlah rintihan kesakitan ataupun kesedihan—oh, bukan!—itu adalah suara cekikan lemah yang datang dari jiwa yang dilimpahi perasaan kagum. Aku tahu benar suara itu. Selama bermalam-malam, tepat saat tengah malam, ketika dunia tertidur, suara itu mengalir di dalam dadaku, semakin dalam, dengan gaungnya yang mengerikan bak teror yang selalu mengusikku. Sudah kubilang, aku tahu benar suara itu. Aku mengerti apa yang dirasakannya sehingga aku merasa simpati padanya, walaupun di dalam hati aku tertawa. Aku tahu kalau dia telah terbangun dari tadi semenjak mendengar suara ribut yang pertama. Ketakutan semakin membuncah di dalam dirinya. Dia mencoba menganggapnya bukan apa-apa, tapi tidak bisa. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri—“Tidak ada apa-apa, hanya suara angin yang bergerak di cerobong asap—atau hanya seekor tikus yang berlari di lantai,” atau “Itu hanya suara jangkrik yang mengerik satu kali.” Benar, dia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan anggapan-anggapan ini, tapi semuanya sia-sia. Karena Kematian telah mengikuti dalam bayang-bayang di depannya, kemudian menyelimuti korbannya. Dan pengaruh bayangan kasat mata itulah yang membuatnya dapat merasakan—walaupun dia tidak dapat melihat ataupun mendengarnya—kehadiran kepalaku di dalam kamar itu.
Ketika aku telah menunggu lama sekali, dengan sangat sabar, tanpa mendengarnya berbaring kembali, kuputuskan untuk memutar sedikit tuas lenteraku. Kalian tidak dapat membayangkan betapa diam-diamnya kulakukan itu—sampai seberkas cahaya redup menerangi mata sipitnya.
Matanya terbuka lebar! Kemudian aku menjadi kesal saat menatapnya. Tatapannya matanya membuatku bergetar sampai ke tulang sumsum. Tapi aku tidak dapat melihat bagian lain wajah atau tubuhnya selain mata kejinya, karena aku telah mengarahkan cahaya lenteraku tepat ke mata terkutuknya itu.
Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kau keliru menganggap kegilaan dengan ketajaman inderaku, bukan? Sekarang biar kujelaskan, telingaku mendengar sebuah suara rendah, tumpul, dan cepat seperti suara jam yang dibungkus kapas. Aku juga tahu benar suara apa itu. Itu adalah suara degupan jantungnya. Suaranya menaikkan amarahku seperti pukulan drum yang menyemangati para tentara di medan perang.
Tapi aku tetap menahan diri dan masih tidak bergerak. Napasku memburu tak beraturan. Kupegang erat lenteraku agar tidak bergoyang. Kucoba secara pasti mempertahankan cahaya yang menembak ke matanya. Sementara itu degupan jantungnya semakin menggebu. Semakin cepat dan lebih cepat lagi, dan semakin nyaring setiap detik. Dia pasti telah diselimuti oleh rasa takut yang amat sangat besar! Suaranya semakin nyaring setiap saat! Apa kau mengerti? Sudah kukatakan kalau aku mudah cemas. Dan sekarang, tepat saat tengah malam, di tengah-tengah keheningan rumah tua yang mengerikan, terasa sangat aneh saat suara seperti ini membuatku bersemangat menikmati ketakutannya yang tak terkendali. Namun begitu, selama beberapa menit aku masih menahan diriku dan tidak bergerak sedikit pun. Tapi degupannya semakin nyaring! Kurasa jantungnya pasti akan meledak. Dan sekarang kecemasan yang lain merengkuhku—suaranya mungkin dapat terdengar oleh tetangga! Waktu orang tua itu telah habis! Dengan teriakan keras, kuputar penuh tuas lenteraku dan melompat masuk ke dalam ruangan. Dia langsung menjerit tertahan. Dalam sekejap kuseret dia ke atas lantai, dan mengangkat kasurnya yang berat dan membekap tubuhnya dengan itu. Kemudian aku tersenyum riang karena sejauh ini perbuatanku telah selesai. Tapi selama beberapa menit, degupan jantungnya masih berdetak dengan suara teredam. Tapi ini tidak menjengkelkanku. Suaranya tidak akan terdengar melewati dinding. Suaranya akan menghilang setelah beberapa saat. Orang tua itu telah mati. Kugeser kasurnya untuk dapat mengamati mayatnya. Benar, dia telah mati kaku. Kuletakkan tanganku di atas dadanya agar dapat merasakan degup jantungnya selama beberapa menit. Tidak terasa adanya denyut nadi. Dia telah mati. Kini matanya tidak akan lagi menggangguku.
Jika kau masih berpikir aku gila, maka kau tidak akan lagi berpikir demikian saat kujelaskan tindakan cerdik yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam semakin larut, dan aku mengerjakannya dengan cepat namun tetap diam-diam. Pertama, kupisah-pisahkan anggota tubuhnya. Kupotong kepala, lengan, dan kakinya.
Комментарии (0)
Минимальная длина комментария — 50 символов.